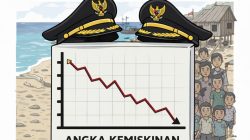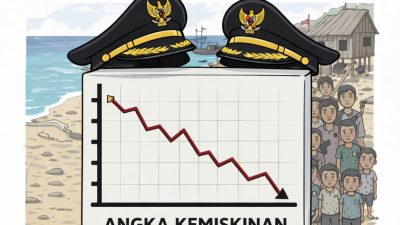(Kasus Jual Beli Tanah di Gapura Timur)
Oleh: Pseudonym*
Nataindonesia.com – Bulan Juli 2025, di Gapura Timur, desa yang biasanya tenang, sebuah peristiwa aneh sekonyong-konyong terjadi dan membuat masyarakat terheran-heran. Seorang peternak berinisial M yang sudah berusia sepuh, tiba-tiba menjual tanahnya kepada S, inisial dari seorang tokoh terpandang di desa ini. Tanah itu, menurut sumber yang sudah terkonfirmasi, terjual dengan harga Rp. 1.500.000, dengan luas sekian meter persegi dan sejumlah tanaman yang tumbuh di atasnya.
Tentu orang menjual tanah bukan perkara asing di desa ini, sebelumnya pun banyak orang menjual tanah, namun tidak memiliki nilai berita karena penjualan terjadi secara wajar, legal dan saling rela di antara dua pihak. Penjualan tanah kali ini berbeda, selain karena harganya yang dianggap murah, juga lebih-lebih proses atau tahapan selama negosiasi yang berlangsung begitu cepat, seperti orang menjual ikan di pasar, ditawar, sepakat, dibayar, lalu pulang.
Pertama, mari kita lihat konstruksi perkara penjualan tanah ini secara kronologis. Siang itu, setelah shalat Jum’at, S mengajak M ke kebun dengan maksud mencari tahu dimana batas tanah masing-masing. Kebetulan tanah S berbatasan langsung dengan tanah M, sehingga M mau saja mengikuti ajakan S. Sesampainya di lokasi, entah bagaimana tiba-tiba M sepakat menjual tanahnya kepada S, dengan harga Rp. 1.500.000. Padahal awalnya M tidak sedang menawarkan tanahnya kepada S.
Kesepakatan penjualan tanah ini terjadi tanpa pengetahuan istri M, atau bahkan anak M sendiri yakni I, yang semestinya ikut diberitahu jika memang S hendak membeli tanah miliknya. Kenapa mesti diberi tahu, karena anggapan di desa ini dan mungkin di seluruh negeri tanah adalah aset berharga, tidak sama dengan barang libialitas lain seperti pohon bambu misalnya, dimana biasanya M sangat alot dalam negosiasi. Karena itu menjual tanah secara dadakan dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga adalah sebuah fakta yang mesti dipertanyakan.
Tidak adanya kesempatan M untuk sekadar musyawarah kepada istri dan anaknya tentang penjualan tanah itu menjadi fakta bahwa negosiasi tampaknya sengaja dibuat cepat, agar M bisa lebih mudah dipengaruhi. Karena kalau tidak, pasti S akan sabar menunggu dan memberi kesempatan kepada M untuk menghubungi istri dan anak-anaknya terlebih dahulu, termasuk bahkan mengundang tokang tafser agar harga tanahnya dibeli secara layak. Tetapi itu tak terjadi, justru negosiasi dilakukan di tengah kebun yang sepi, bukan di tempat biasa seperti di rumah M sendiri misalnya, atau di tempat lain yang lebih netral dimana ada orang lain yang medampingi M dalam proses negosiasi itu mengingat M adalah orang yang sudah sepuh, buta huruf, orang tak mampu secara eknomi, dan juga bukan orang yang terpelajar seperti pihak pembeli. Sebaliknya di sisi lain, pembeli alias S adalah seorang negosiator ulung, dikenal sebagai kiai, tokoh masyarakat dan termasuk golongan elit desa, dimana setiap kata-katanya selalu didengarkan. Ketika mereka bertarung satu lawan satu dalam arena negosiasi, tentulah secara logis M akan kalah dan dengan mudah dipengaruhi, kalau tidak mau disebut dimanipulasi. Pertarungan di arena negosiasi itu seperti kancil melawan singa, yang satu menjadi mangsa bagi yang lain. Maka yang terjadi, M tidak bisa menolak dengan tawaran S dimana menurut informasi yang tervalidasi awalnya M ditawari Rp. 1000.000, karena tidak bersedia lalu tawaran dinaikan menjadi Rp. 1500.000.
Belakangan menurut sumber yang juga sudah confirmed, akibat kesepakatan M yang sepihak dan terlalu cepat itu, serta tanpa memberitahukan kepada siapapun tentang adanya negosiasi penjualan tanah, I putra dari M, memganggap batal jual beli tersebut. Beberapa hari kemudia dia bersama ayahnya bermaksud mengembalikan uang hasil penjualan itu. Namun hal memilukan terjadi lagi, dia oleh S diminta pengembalian Rp. 10.000.000 dengan alasan tanah itu bersama tanah di sampingnya yang merupakan tanah S sendiri akan dijual kepada orang lain seharga Rp. 150.000.000. Akhirnya mereka berdua pulang dengan keadaan batin jika kita mau berempati tersiksa.
Kegagalan Memahami Nilai Agama
Apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Atau apa yang bisa kita perbuat menghadapi fenomena semacam ini? Dari sudut pandang agama, saya melihat satu hal yang menjadi fakta telanjang dari kasus ini, yakni ketidakadilan dan kedzaliman. Salah satu alasan kenapa S menganggap bahwa pembelian tanahnya sah adalah agama, yakni secara agama, dalam hal ini Fiqh. Dalam pernyataannya ketika musyawarah dengan Pemerintah Desa, S mengklaim bahwa pembelian tanahnya sah secara agama, karena terjadi sesuai syarat rukun jual beli, ada penjual ada pembeli, ada barang, ada harga dan lain semacamnya.
Namun pertanyaannya, bagian dari agama yang mana yang dijadikan rujukan dan sumber nilai? Bukannya agama adalah rahmat bagi seluruh alam? Bagaimana ketika dia menggunakan agama untuk menyerobot lahan orang miskin dan tidak mampu, sementara dia sendiri orang kaya yang hampir tiap tahun membeli tanah? Apakah agama serendah itu, hanya menjadi stempel dari aksi penggusuran dan penyingkiran, hanya menjadi legitimasi bagi aksi dzalim yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan? Ataukah jual beli tanah itu hanyalah bungkus saja dari aksi keji agar pengambilalihan lahan sesuai dengan nilai-nilai agama?
Tampaknya tokoh agama ini sudah lupa akan adanya tulang yang digaris dengan pedang oleh Umar bin Khattab r.a dalam kisah perseteruan antara Amr bin Ash dan seorang Yahudi pemilik gubuk reyot di Mesir sana. Atau mungkin ingat hanya kurang bisa memaknai apa itu berbuat baik dan menjadi bermanfaat bagi orang lain, apa itu berbuat baik bagi fakir miskin dan menghadirkan keadilan bagi sesama. Tulang yang digaris dengan pedang itu sudah menjelaskan kepada kita untuk tidak menganggu apalagi merampas hak dan harapan hidup orang lain, meski orang itu adalah Yahudi sekalipun. Tanah adalah kebutuhan dasar yang setiap orang berhak memilikinya, bahkan jika tak mampu, harus ada orang lain yang membantu. Ini berbeda dengan kebutuhan untuk membeli mobil, kendaraan atau gadget. Ini tentang tanah, hak hidup, hak asasi manusia. Manusia bisa hidup tanpa gadget, tapi tak bisa tanpa tanah.
Klaim Persetujuan
Selanjutnya, jika kita mengubah sudut pandang dari agama ke ethic, faktanya akan lebih terang lagi. Saya ingin memperkenalkan dulu apa itu arti persetujuan, dilihat dari subyek yang memberi persetujuan, dalam hal ini tentu pesetujuan untuk menjual tanah. Karena klaim S adalah, M setuju untuk menjual, makanya jual beli terjadi, dan itu secara hukum sah. Dalam konteks etika dan juga hukum, ada istilah yang dinamai consent yang berarti persetujuan, ada pula istilah assent yang berarti persetujuan. Kedua istilah tersebut maknanya sama, persetujuan. Perbedaannya, perstujuan disebut consent ketika subyek atau individu dinilai mampu dan memenuhi setiap kriteria untuk melakukan persetujuan, seperti orang dewasa, mengerti risiko, menerima informasi lengkap, tidak sedang dimanipulasi, tidak sedang dipengaruhi, tidak sedang diintimidasi, tidak sedang dipaksa atau tidak sedang ditekan. Consent itulah yang diakui sah secara hukum, alias memiliki kekuatan hukum.
Sementara assent juga merupakan persetujuan tetapi dilakukan oleh individu yang tidak kompeten, atau tidak memiliki kekuatan hukum, atau dilakukan oleh orang di bawah pengaruh seseorang sehingga seseorang itu mengalami gangguan kognitif, persetujuan yang dilakukan karena tertekan dan terpaksa, karena sungkan dan tidak bisa menolak misalnya, atau persetujuan dalam kondisi dimana nilai tawar individu yang bersangkutan tidak sebanding dengan orang yang diberi persetujuan. Konsekuensinya, ketika persetujuan bersifat consent, maka sah secara hukum, dan dalam hal ini jual beli juga sah, namun apabila persetujuan itu masuk ketegori assent, maka jual beli itu juga batal, tidak benar secara hukum. Contoh gampangnya adalah persetujuan Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J dalam kasus Sambo yang viral beberapa waktu lalu. Walaupun Eliezer memberi persetujuan untuk menembak, tetapi itu bukan consent, tetapi assent, karena itu Eliezer dihukum ringan.
Maka peristiwa jual beli antara M dan S karena persetujuan itu dilakukan di tempat yang tidak ideal, bukan ruang terbuka yang setara, maka saya yakin persetujuan yang dilakukan M kepada S di tengah kebun yang sepi itu masuk dalam kategori assent, yakni persetujuan yang tidak sah secara hukum. Terlebih beberapa hari setelahnya dia inign mengembalikan uang dari S dan ingin menggagalkan jual beli tersebut. Hal ini berbeda misalnya ketika seluruh keluarga M telah berembuk dan menghasilkan sebuah persetujuan yang bulat, barulah itu disebut consent yang valid secara hukum. Hal ini sebenarnya bukan persoalan harga tanahnya yang murah, tetapi kepada persetujuan untuk menjual.
Jadi, klaim S bahwa jual beli tanahnya dengan M sah secara hukum bagi saya adalah klaim sampah. Klaim tidak berdasar baik secara moral agama maupun secara hukum formal. Klaim tersebut hanya memperburuk citranya di depan manusia, klaim yang menunjukkan kegagalan dalam memaknai agama dan etika.
Wallahu A’lam Bisshawab…..
*Penulis adalah Warga NU Desa Gapura Timur.