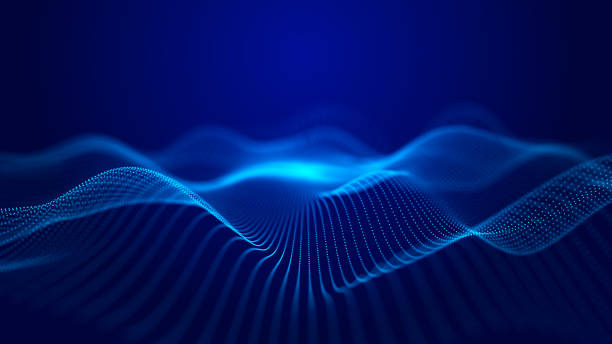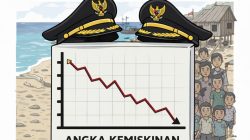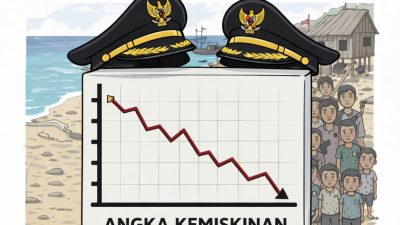Bahasa sebagai Pemicu Energi Genetik Etika
Gila? Mungkin. Tapi kadang, hanya dengan berpikir sejauh ini aku bisa tetap waras.
Di tengah desakan hidup—hutang yang mengejar dan rindu yang menggantung pada seseorang yang bahkan tak pasti—pikiranku justru melompat ke satu tanya yang sulit dijelaskan: mungkinkah bahasa, sejak awal, bukan sekadar alat komunikasi, tapi pemicu getaran yang membentuk kita bahkan sebelum kita memiliki bentuk?
Apakah ini pelarian dari kenyataan? Atau justru jalan keluar yang tak sengaja kutemukan?
Aku merasa sedang berdiri di antara gila dan waras. Bukan karena kehilangan arah, tapi justru karena terlalu banyak arah muncul dalam waktu bersamaan. Di kepalaku berjejalan ide tentang bahasa sebagai pemicu medan, tentang susunan huruf sebagai pembuka aliran energi, dan tentang nutfah—yang bahkan belum disebut manusia—telah menyerap gema dari dunia lewat tubuh ibunya.
Aneh? Bisa jadi. Tapi logikanya perlahan merangkai: setiap huruf menyimpan pola; setiap susunan kata melahirkan medan. Kata bukanlah energi itu sendiri, melainkan isyarat yang memicu pembentukan medan di tubuh. Semakin kompleks susunannya, semakin kompleks pula dampaknya. Dan tubuh, terutama tubuh yang sedang berkembang, menangkap sinyal itu bukan dengan pikiran, tapi dengan getaran halus yang langsung menyentuh sel.
Saat kata-kata dari luar—gumaman, bacaan, doa, tangis, emosi—menyusup lewat tubuh ibu, maka nutfah yang masih setitik kemungkinan itu ikut beresonansi. Bukan secara sadar, tapi secara bioenergetik. Mungkin itulah awal kepribadian yang tak sepenuhnya dijelaskan oleh genetika.
Kukira ini alasan kenapa aku tak bisa lepas dari bahasa. Bukan karena aku sekadar menyukai kata-kata, melainkan karena aku merasa bahasa menyimpan memori lebih purba dari akal. Ia bukan hanya alat untuk menyampaikan pikiran, tapi kunci untuk memahami denyut paling awal dalam diri. Setiap bunyi memiliki jejak; setiap kata menyimpan kemungkinan. Bahkan dalam diam, tubuh kita menyimpan gema dari yang pernah didengar, dirasa, atau diwariskan.
Dan mungkin, dengan memahami bahasa sebagai pemicu, aku sedang belajar memahami diriku sendiri. Karena siapa tahu, gelombang-gelombang yang kita panggil “bahasa” itu, diam-diam telah menciptakan arah sejak kita belum disebut manusia.
Sebagian orang mungkin akan mencibir, “Apa gunanya berpikir sejauh itu saat hidupmu sendiri belum beres?” Tapi bagiku, pikiran-pikiran ini bukan pelarian. Mereka adalah pelampung. Tanpa itu, mungkin aku sudah tenggelam.
Dan kalaupun dunia tak peduli pada kegelisahan semacam ini, tak apa. Aku menuliskannya bukan demi pujian, tapi demi napas. Demi menjaga kewarasan di tengah kegilaan yang pelan-pelan mulai masuk akal. Untuk diriku sendiri. Dan barangkali, untuk satu-dua jiwa lain yang pernah merasa sesak—di antara gila dan waras.
Penulis: Z Bahri – Salah satu redaktur Nataindinonesia.com.