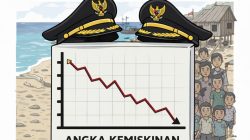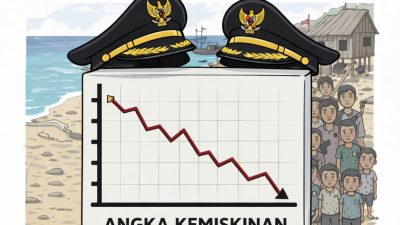Oleh: Awidatir Rahmatilah*
Nataindonesia.com – Penganiayaan terhadap perempuan sering dibayangkan dalam bentuk kekerasan fisik yang terlihat jelas. Padahal, bentuk yang lebih senyap namun sama berbahayanya justru sering bersembunyi di balik budaya, tradisi, atau pola pikir yang diwariskan turun-temurun. Konsep Feodalisme dalam keluarga yang masih lekat dengan mengatas namakan tradisi leluhur yang menempatkan perempuan sebagai pihak kedua, tunduk pada otoritas mutlak figur “kepala keluarga”, dan meminggirkan hak mereka dalam menentukan arah hidupnya sendiri.
Salah satu pandangan filsafat tentang feodalisme berasal dari tokoh filsafat abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau mengkritik sistem feodalisme dengan menyatakan bahwa sistem ini menimbulkan kesenjangan sosial yang besar antara kelas atas dan kelas bawah. Ia menyebut sistem feodalisme sebagai ”sistem tidak adil” karena hanya akan menguntungkan satu pihak.
Menurut Rousseau, feodalisme bertentangan dengan kesetaraan dan kebebasan asli manusia. Sebagai seorang filsuf, ia berpendapat bahwa semua manusia lahir dengan hak dan kebebasan yang sama. Namun, sistem feodalisme justru menempatkan kelas atas sebagai penguasa dan kelas bawah sebagai subjek yang harus taat kepada mereka. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan yang seharusnya ditegakkan dalam sistem sosial, khususnya keluarga.
Berdasarkan data laporan pemberdayaan masyarakat “Wiraraja Mengabdi untuk Negeri”, yang ditulis oleh Nailiy Huzaimah, S.Kep, Ns, M.Kep dkk. Realitas ini terlihat jelas di Desa Lapa Daya, Kecamatan Dungkek. Minat siswa di desa tersebut dalam melanjutkan pendidikan rata-rata masih tergolong rendah. Pendidikan terakhir sebagian besar siswa hanya sampai tingkat MA (Madrasah Aliyah), dengan adanya masalah feodalisme keluarga. Bahkan di salah satu sekolah di desa tersebut yakni Yayasan Mahwil Ummiyah, terdapat siswa yang menikah ketika masih duduk di bangku sekolah. Miris, ketika perempuan dipaksa dalam mematuhi setiap lingkar kekuasaan orang tua, tidak diberi kesempatan dalam memilih bahkan menyuarakan pemikiran yang dimiliki. Pernikahan dini yang dibiarkan terjadi ini berdampak terhadap kognitif perempuan.
Sejak awal tahun 2025 hingga memasuki bulan kemerdekaan ini, kita masih menyaksikan bagaimana hak perempuan diabaikan. Hak untuk memilih, hak untuk belajar, bahkan hak untuk bersuara kerap dibatasi. Dengan dalih adat istiadat, tafsir agama yang sempit, atau stigma sosial. Serta pakasaan” orang tua Akibatnya, potensi perempuan terhenti bukan karena ketidak mampuan, tetapi karena batasan hak yang sengaja dilakukan.
Sebagai mahasiswa, saya memandang ini bukan sekadar persoalan sosial, tetapi pelanggaran konstitusi yang nyata. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) jelas menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Artinya, setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa diskriminasi.
Tidak berhenti di situ, UU HAM Pasal 5 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama. Maka, ketika seorang perempuan tidak diberikan kesempatan belajar, dipaksa menikah, atau dilarang berpendapat, itu bukan hanya masalah moral, tetapi juga pelanggaran hukum.
Hak atas pendidikan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 dan diperjelas dalam UU Sisdiknas adalah hak fundamental. Pendidikan bukan hadiah yang boleh diberikan atau dicabut oleh keluarga akan tetapi adalah kewajiban negara untuk memfasilitasi dan kewajiban masyarakat untuk mendukung.
Mengutip dari Amnesty International Indonesia. mengingatkan bahwa kesetaraan gender adalah prasyarat mutlak bagi pemenuhan seluruh hak asasi manusia. Perempuan bukan hanya objek belas kasihan, melainkan subjek yang memiliki hak penuh atas kebebasan, pilihan hidup dan akses yang sama terhadap sumber daya.
Dengan hal ini saya menekankan bahwa diam terhadap diskriminasi berarti ikut menghalalkan penindasan. Memaklumi feodalisme dalam keluarga sama saja dengan mengkhianati semangat kemerdekaan yang kita rayakan setiap Agustus. Kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan bangsa asing, tetapi juga bebas dari rantai pemikiran sempit yang mengekang potensi manusia terutama perempuan.
Merdeka bagi perempuan adalah ketika ia bisa memilih, belajar, dan berkarya tanpa takut dihakimi, tanpa khawatir haknya dirampas, dan tanpa harus meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri.
*Kader HMI Cabang Sumenep, Komisariat Universitas PGRI Sumenep