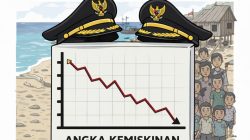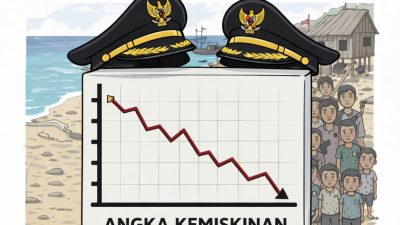Oleh: Moh Riyadi*
Ahad, 17 Agustus 2025 tepak pukul 10:17 Wib, umur Indonesia genap 80 tahun. Semua pelosok Indonesia masyarakat menyambut merah putih dengan segenap doa dan harapan.
Delapan puluh tahun kemerdekaan bukanlah sekadar angka yang ditorehkan dalam kalender sejarah. Ia adalah perjalanan panjang yang ditandai darah, air mata, dan doa; sebuah rentang hidup bangsa yang pernah menjadi korban penindasan, lalu berani berdiri dengan satu kata: Merdeka.
Namun, apa arti merdeka setelah delapan puluh tahun? Pertanyaan ini penting, karena sering kali kita hanya merayakan kemerdekaan sebagai ritual tahunan, tanpa berani bercermin pada wajah bangsa hari ini.
Merdeka, jika dilihat dari sisi sejarah, berarti bebas dari penjajahan asing. Tetapi pada dimensi kehidupan sehari-hari, merdeka seharusnya berarti bebas dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, dan rasa rendah diri. Apakah bangsa ini sudah lepas dari semua itu?
Kenyataan menunjukkan: perjuangan belum selesai. Kesenjangan sosial masih lebar, pendidikan masih menjadi hak istimewa bagi sebagian, dan kekuasaan seringkali masih lebih berpihak pada kepentingan kelompok daripada martabat rakyat banyak. Dalam ruang-ruang seperti inilah kita menemukan bentuk baru dari “penjajahan”—bukan oleh bangsa asing, melainkan oleh sistem dan mentalitas kita sendiri.
Delapan puluh tahun kemerdekaan seharusnya menjadi titik balik. Indonesia bukan lagi bangsa yang sekadar bertahan hidup (survival nation), melainkan bangsa yang mampu merancang visi peradaban. Nusantara kaya sumber daya, tetapi kekayaan itu hanya berarti jika mampu diolah menjadi kesejahteraan, ilmu, dan karya. Sejarah tidak memberi hadiah kepada bangsa yang sekadar menjadi “pasar”, melainkan kepada mereka yang berani melahirkan gagasan dan peradaban.
Merdeka, pada akhirnya, adalah proyek batin dan sosial sekaligus. Ia menuntut keberanian untuk membebaskan diri dari feodalisme pikiran, dari mentalitas pesanan, dari ketakutan untuk berbeda. Merdeka berarti sanggup berjalan dengan tegak di hadapan dunia, tanpa kehilangan akar, tanpa kehilangan kebijaksanaan lokal yang menjadi jantung Nusantara.
Delapan puluh tahun bukanlah akhir, melainkan awal dari babak yang lebih berat: babak mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk yang paling nyata—keadilan sosial, martabat manusia, dan keberanian membangun masa depan.
Indonesia telah berdiri delapan puluh tahun. Pertanyaannya kini bukan lagi, “Siapa musuh kita dahulu?” melainkan, “Apa yang masih membelenggu kita hari ini?” Jawabannya ada pada keberanian kita untuk jujur, untuk belajar, dan untuk menulis babak baru dengan tinta kerja dan kebijaksanaan.
Merdeka, jika sungguh-sungguh dijalani, bukanlah slogan. Ia adalah api. Dan api itu harus terus dijaga, agar bangsa ini tidak hanya hidup dari kenangan masa lalu, tetapi juga dari visi yang akan menerangi dunia.