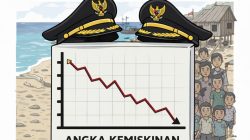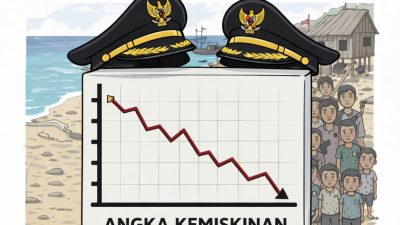ESAI KEBANGSAAN
Kita telah terlalu lama menjadi bangsa yang fasih dalam meniru.
Piawai dalam menyusun kutipan. Lincah dalam menjajakan istilah asing yang belum sempat dijatuhkan ke tanah, dibaui debu, digumamkan lewat lidah ibu.
Barangkali, di situlah tragedi kita bermula:
Kita terbiasa berbicara dengan bahasa yang bukan milik kita.
I
Mula-mula, penjajahan datang lewat bedil dan sistem. Kini, ia datang lewat seminar. Lewat kurikulum. Lewat buzzword.
Kita tidak lagi dijajah dengan paksa, tapi diajari merasa tertinggal bila tak mengadopsi nilai mereka.
Kata “modern” kita pelajari dari luar,
dan sejak itu, kita mengukur segala dengan skala yang tidak kita ciptakan sendiri.
Kita menyebut kearifan kita sendiri sebagai “tradisional” dengan nada setengah malu.
Apakah kita sadar…
bahwa bahkan dalam rasa minder itu, ada sisa-sisa hipnosis sejarah?
II
Sekarang ini, anak-anak sekolah bisa menyebutkan tokoh-tokoh revolusi industri,
tapi gagap saat ditanya siapa yang merumuskan filsafat gotong royong.
Bisa menjelaskan ESG dan geopolitik,
tapi terbata-bata ketika diminta menjelaskan falsafah leluhur.
Kita tak lagi menggali tanah,
karena kita terlalu sibuk memindahkan batu bata wacana dari barat.
Kita membangun istana ide yang kokoh—tapi kosong—karena tak punya akar.
Kita kehilangan arah,
karena kehilangan bahasa yang bisa menunjuk siapa diri kita di dunia ini.
III
Yang menyedihkan:
bahkan bahasa pun sudah jadi ladang kolonial baru.
Kita tergesa menerjemahkan nilai-nilai lokal ke dalam bahasa akademik global,
tapi tak sadar makna-makna paling subtil terkikis dalam prosesnya.
Kita kehilangan kata “rasa” ketika menggantinya dengan “sensation”.
Kita kehilangan “batin” ketika menyamakan segalanya dengan “mental”.
Kita bukan hanya kehilangan kata.
Kita kehilangan struktur berpikir yang membentuk cara kita hidup sebagai manusia.
Kita hilang…
dalam terjemahan yang kita anggap sebagai kemajuan.
IV
Di layar televisi, di panggung konferensi, di media sosial—
kita pamerkan jargon: inclusive growth, futureproofing, resilience, smart nation…
Padahal desa-desa kita masih butuh puskesmas, bukan panel diskusi.
Kita terlalu pintar dalam presentasi,
tapi terlalu malas untuk kembali mendengar suara sungai,
suara ibu, suara luka-luka lama yang belum juga sembuh.
Kita terlalu terdidik untuk menjadi penjajah terhadap diri kita sendiri.
Bangga ketika mirip luar.
Minder saat disebut ndeso.
V
Aku menulis ini bukan karena benci dunia global.
Aku menulis ini karena aku mencintai akar.
Karena sebuah bangsa yang kehilangan bahasa ibunya,
akan kehilangan arah jiwanya.
Karena sebuah bangsa yang terlalu sering menerjemahkan tanpa merenungkan,
akhirnya tak tahu lagi… apa yang sebenarnya ingin ia katakan.
Cermin Diri
Ini bukan esai untuk dibaca. Ini tamparan.
Untuk siapa saja yang masih merasa bisa hidup tanpa mengenali dirinya.
Untuk siapa saja yang mengira kemajuan hanya bisa dicapai dengan menjadi seperti mereka.
Kalau kamu membacanya dan merasa tak nyaman—maka mungkin kamu masih punya nyawa.
Jangan buru-buru menerjemahkan esai ini.
Mungkin, kamu justru harus menerjemahkan kembali dirimu sendiri.
Penulis: Arka Sadhana Ziyad